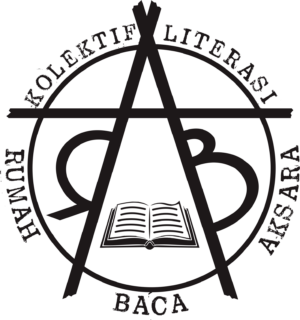Oleh: Leonardo Alessandro Lako Dhei
Dalam era digital yang ditandai oleh kecepatan informasi, kemajuan teknologi dan dominasi media sosial, kemampuan berpikir kritis serta kepekaan moral tidak lagi dapat dipandang sebagai kemewahan intelektual.
Keduanya justru menjadi kebutuhan mendesak dalam kehidupan sehari-hari.
Informasi kini tidak hanya beredar dengan cepat, tetapi juga bersaing untuk mendapatkan perhatian publik melalui mekanisme viralitas yang sering kali mengutamakan daya tarik emosional dibandingkan kebenaran faktual.
Kondisi ini kian kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI. Ia menunjukkan bagaimana teknologi modern mampu mewujudkan hal-hal yang dulu dianggap mustahil.
Dengan AI beserta beragam kemudahan yang ia tawarkan, pencarian terhadap kebenaran menjadi kian menantang.
Berbagai aplikasi AI bisa memproduksi konten, lalu membuatnya jadi viral dan bisa mengecoh publik, seolah-olah itu adalah kebenaran faktual.
Kita pun dihadapkan pada tantangan serius: bagaimana membedakan antara apa yang benar, apa yang dimanipulasi dan apa yang sekadar populer.
Dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, persoalan ini menjadi semakin krusial.
Tanpa kemampuan berpikir kritis, individu berisiko tereduksi menjadi konsumen pasif terhadap arus informasi digital yang terus mengalir tanpa henti.
Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka reflektif yang memungkinkan manusia tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menilai, menguji dan mempertanggungjawabkannya.
Antara Kebenaran dan yang Viral
Meskipun lahir berabad-abad sebelum kemunculan internet dan media sosial, pemikiran filsuf sekaligus teolog seperti Agustinus (354-430) menawarkan landasan konseptual yang kuat untuk memahami krisis kebenaran di era digital.
Agustinus tidak memahami kebenaran sebagai sesuatu yang ditentukan oleh konsensus sosial atau popularitas, melainkan sebagai kesesuaian antara akal budi manusia dan realitas objektif.
Ia membedakan secara tegas antara opinio (pendapat) dan veritas (kebenaran).
Pendapat dapat berubah, dipengaruhi oleh emosi dan tekanan sosial, sedangkan kebenaran bersifat tetap dan menuntut pencarian yang jujur serta reflektif.
Ketika sesuatu dianggap benar hanya karena banyak dibagikan atau disukai, maka standar kebenaran bergeser dari rasionalitas menuju popularitas.
Padahal, baginya, kebenaran tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang mempercayainya, tetapi pada relasinya dengan kenyataan itu sendiri.
Fenomena viralitas di media sosial justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
Informasi menyebar bukan karena validitasnya, melainkan karena kemampuannya memicu reaksi emosional seperti kekaguman, kemarahan atau rasa ingin tahu.
Contoh yang mudah diamati adalah bagaimana kehidupan personal figur publik dan selebritas menjadi komoditas utama dalam ekosistem media digital.
Berita tentang selebritis dapat menyebar luas dalam hitungan jam, meskipun substansi informasinya sering kali minim, demikian juga kontribusi substansialnya terhadap isu sosial.
Faktor penentunya adalah daya tarik emosional dan algoritma, dengan logika keterlibatan (engagement), bukan kebenaran.
Konten yang mampu menarik perhatian akan dipromosikan lebih luas, sementara informasi yang menuntut pemahaman mendalam atau refleksi rasional sering kali tersisih.
Akibatnya, ruang publik digital dipenuhi oleh narasi-narasi dangkal yang viral, sementara kebenaran kehilangan visibilitasnya.
Dalam terang pemikiran Agustinus, budaya media sosial yang menyamakan viralitas dengan kebenaran dapat dipahami sebagai bentuk krisis epistemik.
Ketika sesuatu dianggap benar hanya karena banyak dibagikan atau disukai, maka standar kebenaran bergeser dari rasionalitas menuju popularitas.
Agustinus melihat kecenderungan ini sebagai bentuk keterasingan manusia dari kebenaran sejati, karena manusia berhenti mencari kebenaran dan mulai mengejar pengakuan sosial.
Sayangnya, logika viralitas tidak hanya bekerja dalam ranah hiburan, tetapi juga merambah ke berbagai bidang, termasuk politik.
Dalam dinamika politik Indonesia masa kini, banyak tokoh pemerintahan dan elit politik aktif di media sosial dengan gaya yang menyerupai “selebgram politik.”
Platform seperti TikTok dan Instagram dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan, merespons kritik atau membangun kedekatan emosional dengan pemilih, khususnya generasi muda.
Ada jebakan di sini.
Strategi komunikasi yang mengandalkan media sosial menimbulkan kesan bahwa respons politik lebih dipandu oleh popularitas atau persepsi viral, daripada analisis substansial terhadap isu-isu mendasar.
Kondisi ini diperkuat oleh realitas konsumsi berita di Indonesia. Sebagian besar masyarakat mendapatkan berita melalui media sosial.
Merujuk pada laporan Reuters Institute for the Study of Journalism Digital News Report 2024, sekitar 60% penduduk Indonesia mengaku mendapatkan berita dari platform seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan Instagram.
TikTok, khususnya, mengalami lonjakan popularitas sebagai sumber berita, naik 7 poin persentase dari 22% pada tahun sebelumnya menjadi 29%.
Ketika media sosial menjadi sumber utama berita, maka logika algoritma menentukan wacana publik.
Informasi yang menjual secara visual dan emosional lebih menentukan persepsi publik dibanding fakta.
Dimensi Etis Kebenaran
Salah satu pokok penting dari pemikiran Agustinus adalah penekannya pada dimensi etis dari kebenaran.
Bagi dia, mencari dan mengatakan kebenaran bukan hanya persoalan intelektual, tetapi juga tanggung jawab moral.
Dalam konteks media sosial, hal ini berarti bahwa menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan bukan sekadar kesalahan faktual, melainkan tindakan yang bermasalah secara etis karena dapat merugikan orang lain dan merusak kepercayaan publik.
Fenomena infodemik—kebingungan massal antara fakta dan fiksi—menjadi konsekuensi nyata dari krisis ini.
Ketika bukti dan sensasi diperlakukan setara, masyarakat kehilangan dasar bersama untuk berdiskusi secara rasional.
Agustinus juga menekankan pentingnya martabat manusia. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki jiwa, kehendak bebas dan kapasitas moral yang tidak dimiliki oleh mesin apapun.
Di tengah ketertarikan kita kepada kecanggihan teknologi, kita harus tetap menempatkan martabat manusia pada posisi yang tak tergantikan.
Teknologi harus dilihat sebagai alat yang meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai entitas yang bisa menggantikan nilai moral atau spiritual kita.
Karena itu, tantangan terbesar di era digital bukan lagi soal teknologi, melainkan bagaimana kita menggunakannya
Menjadi pengguna media sosial yang cerdas berarti tidak sekadar mengonsumsinya. Kita mesti mempertanyakan sumber, mencari fakta dan menahan diri sebelum menyebarkan sesuatu yang belum terverifikasi.
Di sini, kita bisa bisa memakai cara berpikir filsafat, yang tidak menawarkan jawaban instan, tetapi bertanya, menguji asumsi dan membedakan antara opini, apa yang populer dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di era AI, di mana jawaban bisa didapatkan dalam hitungan detik, filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar jawaban cepat, tetapi mengejar pemahaman yang mendalam tentang jawaban itu.
Kita belajar bertanya bukan sekadar “apa yang dikatakan AI?” tetapi “mengapa jawaban itu penting bagi manusia?”
Jika kita ingin memanfaatkan teknologi secara bijak agar teknologi tidak menjadi tuan atas kita, maka kita perlu terus mempertahankan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kepekaan moral.
Ini bukan sekadar tugas akademik, tetapi panggilan etis bagi siapa pun yang hidup di zaman ini.
Leonardo Alessandro Lako Dhei adalah Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Editor: Dominiko Djaga