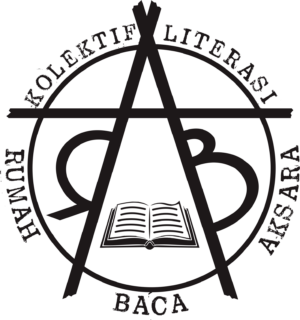YBR adalah siswa yang periang. Di sekolahnya, SD Negeri Rutojawa di Kabupaten Ngada, ia dikenal aktif dan berprestasi. Di rumah ia biasa membantu neneknya menjual sayur, ubi dan kayu bakar.
Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kesehariannya yang tampak biasa, anak berusia 10 tahun itu memilih mengakhiri hidupnya secara tragis dengan bunuh diri. Pilihannya dipicu ketidakmampuan ibunya membeli buku dan pena seharga sepuluh ribu rupiah.
Dalam surat yang ditulis menggunakan bahasa daerah, YBR mengungkapkan perasaan bahwa ia menjadi beban bagi keluarga. Perasaan itulah yang mendorongnya mengambil keputusan yang menyayat hati.
Tragedi ini menjadi ironi bagi dunia pendidikan tanah air. Saat dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbanyak, masih ada anak yang tidak bisa membeli buku dan pena.
Saya teringat akan kata–kata Malala Yousafzai, aktivitas pendidikan Pakistan yang gigih memperjuangkan hak anak perempuan untuk bersekolah, ”One child, one teacher, one pen, and one book can change the world.” Seorang anak, seorang guru, sebuah pena dan buku dapat mengubah dunia.
Namun dalam kenyataan pahit ini, akses terhadap buku dan pena ternyata masih menjadi kemewahan bagi anak.
Pada titik ini, program MBG yang dibanggakan pemerintahan Prabowo – Gibran perlu digugat. Apakah intervensi gizi sudah berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan?
Makan Bergizi Gratis
MBG, program yang implementasinya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN), merupakan salah satu janji utama Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye.
Program ini diklaim dirancang untuk memperbaiki gizi anak dan mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Sejak digulirkan pada awal Januari 2025, MBG diklaim sudah menjangkau 55,1 juta dari target 82,9 juta anak.
Pada 2025, MBG menelan biaya Rp 71 triliun, sementara tahun ini Rp. 335 triliun.
Dalam APBN 2026, sebagian besar anggarannya dialokasikan dari anggaran pendidikan, dengan tambahan dari sektor kesehatan dan fungsi ekonomi. Pemerintah daerah dapat mendukungnya melalui APBD, tetapi bukan sebagai sumber utama.
MBG sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi karena mengeruk anggaran yang besar dari dana pendidikan. Padahal, alokasi untuk makanan tidak termasuk dalam ketentuan dana pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Berkurangnya ruang fiskal pendidikan karena dialihkan untuk MBG tentu mengorbankan banyak hal, terutama peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan bantuan pendidikan.
Menurut Adrian Nalendra, peneliti Ekonomi GREAT Institute, penurunan anggaran pendidikan turut menggerus kualitas layanan pendidikan. Intervensi gizi berjalan cepat, sementara input pedagogis melemah; perut kenyang tetapi kualitas belajar stagnan.
Program yang dibangga–banggakan Prabowo sebagai investasi untuk masa depan bangsa ini terus juga mendapat sorotan publik, setelah berbagai kasus keracunan.
Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang 2025, tercatat 12.658 siswa yang keracunan. Dalam periode 1 hingga 13 Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 1.242 orang yang menjadi korban. Kasus-kasus itu tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Tingginya angka korban keracunan adalah bukti lemahnya pengawasan keamanan pangan dalam program ini.
Prabowo sendiri juga mengakui masalah tersebut. Namun baginya, jumlah kasus keracunan sangat kecil jika dibandingkan jumlah penerima manfaat, “sekitar 0,0009%.” Pandangan berbasis persentase semata ini berisiko mengaburkan dimensi kemanusiaan dari setiap kasus.
Kajian Nalar Institute terhadap pelaksanaan MBG selama satu tahun juga menunjukkan berbagai persoalan struktural, berupa monopoli, lemahnya pengawasan dan informasi publik yang tertutup
Sekolah Gratis
Amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Konstitusi kita juga secara tegas menyatakan negara wajib menyediakan pendidikan gratis bagi semua anak bangsa.
Namun secara faktual, hingga di usia kemerdekaan ke-81, pendidikan gratis hanya sekedar wacana. Gaung pendidikan gratis terdengar nyaring, tapi sepi dalam implementasi.
Pemerintah memang sudah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, intervensi ini hanya untuk memenuhi biaya operasional sekolah.
Dengan dana BOS, siswa dibebaskan dari biaya langsung pendidikan seperti biaya ujian, biaya buku paket pelajaran, biaya gaji guru, biaya perlengkapan praktik dan lain-lain.
Namun, orang tua masih harus menanggung biaya tidak langsung, seperti seragam, buku tulis dan pena, tas, sepatu, transportasi dan biaya hidup.
Jika dikalkulasi, biaya tidak langsung pendidikan ini lebih mahal dari biaya operasional sekolah yang ditanggung dana BOS.
Bagi keluarga miskin (ekstrem), biaya ini sangat memberatkan. Memutuskan antara memenuhi kebutuhan hidup setiap hari atau membayar biaya sekolah anak adalah pilihan dilematis.
Cermin Kegagalan Negara
Tragedi YBR adalah fakta pilu bahwa kemiskinan ekstrem membatasi kemampuan keluarga memberi akses pendidikan bagi anak.
Anak–anak dari keluarga miskin selalu tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
Tragedi ini adalah cermin kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan.
Mengapa untuk program populis seperti MBG, pemerintah berani menggelontorkan anggaran triliunan rupiah?
Ini bukan soal negara mampu atau tidak. Ini menyangkut keberpihakan. Pemerintah tidak punya political will dalam menunaikan amanah konstitusi mencerdaskan anak bangsa.
Kematian YBR menggugat keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan anak bangsa. Selain menggoreskan duka, kepergiannya juga meninggalkan pesan bagi pemerintah bahwa anak lebih membutuhkan pendidikan gratis ketimbang MBG.
Gerardus Kuma adalah Guru SMPN 3 Wulanggitang, Hewa, Flores Timur
Editor: Dominiko Djaga