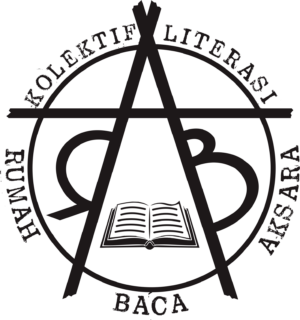Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang intinya berisi soal pemisahan terlaksananya pemilu nasional dan lokal, wacana mengembalikan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengemuka.
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar pada Juli 2025 saat peringatan Ulang Tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Sejak itu, ide ‘liar’ tersebut terus menggelinding.
Lalu, bukannya fokus menangani banjir di Aceh dan Sumatera yang dinilai lamban, Presiden Prabowo Subianto malah kembali mengangkat isu ini saat berpidato dalam kegiatan Dies Natalis Partai Golongan Karya (Golkar) pada 5 Desember 2025.
Gayung bersambut, Bahlil Lahadalia pun sepakat dan meminta agar ini segera menjadi agenda pembahasan Revisi Undang-Undang oleh DPR pada 2026. Partai Golkar kemudian mengusulkan pilkada tak langsung ini setelah menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional I pada 20 Desember 2025.
Sejauh ini, partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung wacana ini dengan alasan serupa: pilkada langsung dianggap mahal, rawan politik uang dan dapat meretakkan kohesi sosial.
Dari delapan partai politik yang ada di parlemen, hanya PDIP Perjuangan yang secara tegas menyatakan penolakan.
Penolakan serupa juga muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Republikanisme dan Kedaulatan Rakyat
Dalam tradisi pemikiran politik (Sahdan, 2025), terang benderang menunjukkan bahwa republikanisme sejak awal lahir sebagai kritik terhadap kekuasaan yang terlepas dari kontrol publik.
Plato, dalam The Republic (Allan Bloom, ed., Basic Books, 1991), memandang negara sebagai tatanan etis yang bertujuan mewujudkan keadilan.
Meskipun istilah “republik” dalam karya ini merupakan terjemahan dari politeia—yang lebih dekat pada makna konstitusi atau rezim—gagasan Plato memberikan fondasi bahwa kekuasaan hanya sah bila dijalankan demi kebaikan bersama.
Dalam kerangka tersebut, republik dipahami sebagai upaya kolektif untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat berkontribusi pada stabilitas tatanan publik. Tanpa orientasi kepentingan umum, kekuasaan kehilangan dimensi etisnya dan cenderung melahirkan ketidakadilan.
Niat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD, dalam konteks ini, dapat dibaca sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar republikanisme yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Dalam Politics (Cambridge University Press, 1998), Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon—makhluk yang hanya dapat mencapai kebaikan tertinggi dalam komunitas politik. Karena itu, kekuasaan harus tetap berakar pada kehendak rakyat.
Pemilihan langsung, terlepas dari berbagai kekurangannya, merupakan salah satu instrumen penting untuk menyalurkan hak politik warga negara.
Aristoteles juga membedakan secara tegas antara oikonomia—pengelolaan demi kecukupan bersama—dan chrematistike, yakni pengejaran akumulasi kekayaan tanpa batas.
Pembedaan ini mengingatkan bahwa republik sejati harus membatasi dominasi logika ekonomi agar tidak mengorbankan kepentingan publik.
Namun, prinsip tersebut kerap direduksi menjadi persoalan efisiensi biaya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa argumen yang menjadikan ongkos pilkada sebagai pembenar sistem tak langsung mengandung logika bermasalah karena menyempitkan demokrasi menjadi sekadar hitung-hitungan anggaran.
Jika biaya dijadikan tolok ukur utama, anggaran pilkada yang diperkirakan sekitar Rp37 triliun justru jauh lebih kecil dibandingkan biaya Pemilu Presiden dan Legislatif yang mencapai Rp71,3 triliun.
Bahkan, anggaran pilkada juga lebih rendah dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp71 triliun pada 2025 dan direncanakan meningkat signifikan pada tahun berikutnya.
Penyempitan demokrasi menjadi urusan teknokratis semacam ini berbahaya bagi republik.
Cicero, dalam On the Commonwealth and On the Laws (Cambridge University Press, 1999), mendefinisikan republik sebagai res publica—urusan milik rakyat—yang hanya dapat bertahan bila kekuasaan dijalankan demi keadilan tertinggi (summa iustitia) dan kesejahteraan umum (bonum commune).
Ketika keputusan politik dipisahkan dari kehendak rakyat, republik membuka ruang bagi dominasi segelintir elite.
Pengalaman masa Orde Baru menunjukkan bagaimana mekanisme pemilihan tak langsung pernah menjadikan DPRD sebagai perpanjangan tangan kekuasaan pusat melalui dominasi partai penguasa dan militer, sehingga menyingkirkan aspirasi rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Selain itu, mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari arsitektur otoritarianisme pemerintahan yang menyingkirkan rakyat, menyuburkan KKN dan membuat kebijakan tidak responsif.
Situasi ini memperlihatkan bahwa penghapusan partisipasi langsung bukanlah solusi atas problem demokrasi, melainkan justru memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Kesadaran akan bahaya dominasi ini kemudian dirumuskan kembali dalam pemikiran republikan kontemporer.
Philip Pettit, melalui Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford University Press, 1997), menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah kondisi non-dominasi—yakni ketika warga tidak tunduk pada kehendak sewenang-wenang elite politik maupun oligarki.
Dalam kerangka inilah, Reformasi 1998 dan penerapan pilkada langsung sejak 2005 dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan legitimasi kekuasaan lokal kepada rakyat.
Jalan Perbaikan
Mengembalikan pilkada lewat DPRD merupakan solusi instan yang mengorbankan prinsip dasar republik bahwa kekuasaan, apapun risikonya, harus tetap bersumber dari kehendak rakyat sekaligus sama sekali tidak menyentuh akar persoalan.
Selama ini, partai politik yang sebetulnya mampu menjalankan fungsi republikan yaitu sebagai ruang artikulasi kepentingan publik dan pendidikan politik warga malah menjauh dari itu.
Sebaliknya, persoalan yang terjadi adalah lemahnya kaderisasi, rekrutmen yang sangat pragmatis dan lebih berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan elektoral dalam jangka pendek, alih-alih menjadi ‘kawah candradimuka’ untuk membentuk kepemimpinan politik.
Marak terjadi, figur-figur tertentu direkrut menjelang pilkada dan bahkan sampai terpilih hanya karena kemampuan finansial dan popularitas, entah itu sebagai pengusaha maupun selebritas.
Padahal, mereka tidak melalui proses proses penggemblengan ideologis yang memadai, bukan pula karena rekam jejak pengabdian atau kapasitas kepemimpinan.
Aspirasi konstituen ditempatkan pada urusan kesekian, sedangkan mahar politik, negosiasi elektabilitas dan kompromi elit menjadi penentu utama.
Kekuasaan kepala daerah akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan elite partai, bukan pada mandat rakyat.
Karena itu, seharusnya hal yang mendesak untuk dilakukan adalah memperketat dan menata pendanaan politik agar tidak bergantung pada modal besar, mereformasi partai politik agar lebih demokratis dan terbuka dalam rekrutmen kandidat, serta memperkuat lembaga pengawasan agar praktik transaksional dapat ditekan secara sistematis.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kekuasaan seorang pemimpin bahkan presiden pun memiliki batas, karena kekuasaan yang abadi adalah kekuasaan rakyat—yang di atasnya lagi adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
Jika wacana mengembalikan Pilkada tak langsung semata-mata bertujuan melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu, maka sejarah menunjukkan bahwa jalan semacam itu hanya akan berujung pada keruntuhannya sendiri.
Vansianus Masir adalah Pemimpin Redaksi Lenbaga Pers Mahasiswa (LPM) TEROPONG sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) ‘APMD’ Yogyakarta.
Editor: Ryan Dagur