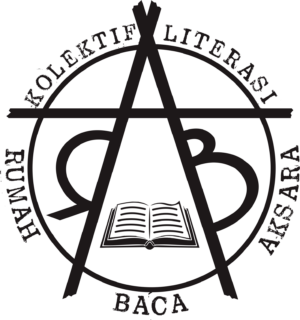Floresa.co – Nyaris dua pekan Fransiska Lete Plue atau Iska mengungsi ke rumah keluarganya di Desa Timu Tawa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
Bersama sang ayah, ia berangkat ke Timu Tawa dari kampung mereka di Wolorona, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur pada 1 Januari pagi.
“Kami tak bawa pakaian, hanya sertifikat rumah, sertifikat tanah dan ijazah,” katanya kepada Floresa.
Sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur pada malam pergantian tahun, ia belum kembali bersekolah.
Ia pun tak tahu apakah sekolahnya telah kembali dibuka. Tak ada kabar apapun dari pengelola sekolah.
Lebih dari dua pekan tak bersekolah, Iska mulai rindu membaca pelbagai buku dan bertemu teman-teman sebaya di sekolahnya.

Iska merasa beruntung karena “bertemu beberapa teman baru di Dungan.”
Mereka meminjaminya buku-buku yang membuat ia “sedikit melupakan kesedihan” lantaran berada jauh dari kampung halaman.
Beberapa buku pinjaman merupakan buku mata pelajaran sekolah.
Bagi Iska, “dapat kembali membaca buku-buku itu membuat saya tidak lupa akan pelajaran yang diberikan di sekolah.”
Iska tercatat sebagai siswa Program Pendidikan Kesetaraan [Paket] B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM] Sandamai, Kampung Kanada, Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur.
Kampung Kanada tak terdampak erupsi Lewotobi Laki-Laki. Namun, sejumlah murid berasal dari dua kecamatan terdampak erupsi, masing-masing Wulanggitang dan Ilebura.
“Kami [para murid] terpencar, tak saling tahu mengungsi ke mana,” katanya.
Mereka juga tak bisa saling memberi kabar “karena banyak yang tak punya ponsel, termasuk saya.”
Diajak Bersekolah di Desa Pindahan
Cerita Iska mirip dengan pengalaman Marlen dan saudara kembarnya, Merlin.
Sepasang anak kembar berusia 13 tahun itu tinggal di Dusun Bawalatan, Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang.

Pada 1 Januari, keduanya bersama orang tua mereka mengungsi ke rumah kerabat di Dusun Bubuk, Timu Tawa.
“Kami tak sempat kemas seragam sekolah dan buku pelajaran,” kata Marlen, “karena bapak mengira esoknya kami bisa pulang.”
Keduanya tercatat sebagai siswa kelas VII di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wulanggitang. Selepas libur Natal dan Tahun Baru, mereka sebetulnya mulai bersekolah pada 4 Januari.
Namun, sejak 1 Januari sekolah mereka turut digunakan sebagai pos pengungsian.
“Kami dengar, banyak keluarga teman-teman kami yang mengungsi ke sana,” kata Marlen.
Menumpang sementara di Bubuk, mereka akhirnya memiliki teman-teman baru, tak ubahnya Iska di sekitar rumah kerabatnya.
Kebanyakan teman baru si kembar menimba ilmu di Sekolah Menengah Pertama Katolik [SMPK] St. Antonius Boganatar.
Beberapa teman baru mengajak mereka “ikut ke sekolah.” Tak hanya itu, “kepala sekolah SMPK St. Antonius suruh kami sekolah saja di sana.”
“Tak perlu malu-malu,” kata kepala sekolah seperti diceritakan kembali oleh Marlen, “sementara sekolah di sini saja, tak perlu bayar.”
Meski terbuka jalan bagi mereka untuk kembali bersekolah, Marlen mengaku “tak percaya diri” karena tak punya seragam sekolah, buku pelajaran dan alat tulis.
“Bapak memang beberapa kali pulang ke Bawalatan,” katanya, “tetapi sekadar kasih pakan ternak.”
Ayah si kembar enggan berlama-lama di kampung “karena takut gunung meletus lagi.”
Akhirnya Bersekolah Lagi
Semenjak mengungsi, Iska dan si kembar kerap bertandang ke aula kantor Desa Timu Tawa.
Acapkali kedatangan mereka guna mengambil bantuan, entah sembako atau barang kebutuhan lain.
Suatu kali dalam aula itu mereka bertemu Camat Talibura, Lazarus Gunter. Ia meminta para pengungsi anak–termasuk Iska, Marlen dan Marlin–kembali bersekolah.

Anak-anak usia 6-12 tahun diarahkan ke Sekolah Dasar Inpres Dungan, sedangkan yang berumur hingga tiga tahun di atasnya didorong bersekolah di SMPK St. Antonius Boganatar.
Bersemangat menyambut arahan camat, esoknya mereka memutuskan berangkat ke SMPK St. Antonius.
Hari pertama bersekolah di Timu Tawa, “kerabat antar kami naik sepeda motor.” Hari pertama bersekolah itu pula mereka mendapat lebih banyak teman baru.
Esok paginya mereka memutuskan “berjalan kaki bersama teman-teman baru ke sekolah baru.”
Mereka tak bisa menghitung pasti jarak antara desa pindahan dan sekolah baru, “tetapi sekali jalan kira-kira lima kilometer jauhnya.”
Walaupun tak berseragam sekolah, “kami senang sekali bisa bersekolah lagi,” kata Marlen.
Mereka juga tak merasa iri melihat teman lain mencatat materi dalam buku bawaan dari rumah masing-masing.
“Tak apa ketika yang lain mencatat, sementara kami hanya mendengar penjelasan guru,” katanya.
“Nanti pemerintah bantu sediakan buku untuk kami,” katanya separuh berharap.
Hingga saat ini, terdapat 17 siswa pengungsi yang bersekolah di SMPK St. Antonius. Masing-masing enam siswa pengungsi lainnya mulai bersekolah di SDI Dungan dan SDK Boganatar.
“Kami menyambut baik kedatangan murid dari sekolah-sekolah terdampak erupsi di Wulanggitang, yang untuk sementara mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini,” kata Nesta Tukan, Wakil Kepala Sekolah SMPK St. Antonius Boganatar.
Para guru “berharap mereka segera pulih dari trauma akibat erupsi dan bisa fokus belajar.”
Tanpa memerinci jumlahnya, ia mengatakan “sejumlah di antaranya terdata sebagai murid kelas IX yang sebentar lagi mengikuti rangkaian ujian akhir kelulusan.”
Di tengah-tengah potensi erupsi lanjutan Lewotobi Laki-laki, “para guru berusaha memberikan porsi belajar yang maksimal bagi mereka.”
Hingga 15 Januari, jumlah pengungsi terdampak erupsi bertambah menjadi 6.489 jiwa.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau warga tak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari rekahan kawah gunung itu.