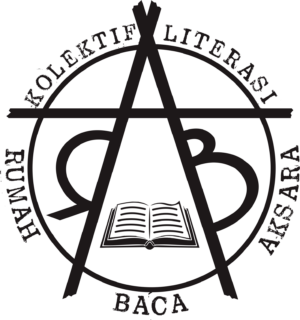Floresa.co – Pendidikan di Indonesia mengalami degradasi yang kuat dan diterpa sejumlah persoalan karena negara belum maksimal memberikan pelayanan kepada warga, demikian kata pembicara dalam diskusi di Yogyakarta baru-baru ini.
Karena itu mahasiswa diminta tidak tinggal diam dan menutup mata terhadap ragam persoalan yang menggerogoti dunia pendidikan.
Berlangsung di Common Room, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa [STPMD] “APMD” diskusi yang diinisiasi Dewan Pimpinan Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia [DPK GMNI] pada 4 Mei itu bertajuk “Transformasi Pendidikan dan Pendangkalan Intelektual di Indonesia.”
Dipandu Yepsi Umbu dan dipantik Marselinus Tanggu Holo, diskusi dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional [Hardiknas] itu diikuti calon anggota, anggota, dan kader DPK GMNI.
Marselinus yang juga merupakan alumni STPMD “APMD” mengatakan pendidikan kita hanya berorientasi untuk mendapat Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi, mendapat pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Akan tetapi, kata dia, “kita alpa mendiskusikan atau menanyakan esensi pendidikan.”
Menurutnya, esensi pendidikan adalah supaya manusia merdeka dalam berpikir, bertindak dan menentukan pilihan hidup dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya.
Marselinus juga menyoroti biaya pendidikan yang dari tahun ke tahun semakin mahal.
Akibatnya, kata dia, masyarakat kecil dengan pendapatan menengah ke bawah sulit mengakses pendidikan.
“Lihat saja, mengurus apa saja di kampus, segala sesuatunya pasti dibayar. Pendidikan kita bukannya naik kelas, malah turun kelas,” ungkapnya.
Ia berkata hanya orang-orang tertentu dengan pendapatan tinggi yang mudah mengakses pendidikan karena mereka didukung kemampuan finansial dan fasilitas yang memadai.
Situasi tersebut, kata dia, menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam mengakses pendidikan.
“Orang yang punya pendapatan tinggi mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, masyarakat kecil mengenyam pendidikan seadanya yang sesuai dengan kemampuan keuangannya,” katanya.
Marselinus mengatakan di tengah biaya yang kian mahal, pendidikan kita juga digerogoti masalah lain yaitu terbatasnya kebebasan akademik. Masalah ini, kata dia, seringkali terjadi di dalam kampus yang masih mempraktikkan feodalisme.
“Dosen menganggap diri sebagai pemenang kebenaran absolut sehingga alergi ketika ada mahasiswa yang mengkritisi cara berpikirnya. Orang yang mengkritik suatu kebijakan dianggap bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan negara justeru mengamini itu,” katanya.
Ia menjelaskan jika ada yang berani membantah, kendati dengan argumentasi yang kuat, maka dosen akan memberi nilai yang tidak sesuai dengan kontrak belajar yang sudah disepakati.
Pemberian nilai, kata dia, tidak berdasarkan penilaian objektif tetapi berdasarkan sentimen.
Ia berkata terhadap situasi itu, mahasiswa tidak boleh diam, tetapi terus menggaungkan suara-suara kritis.
Jika mahasiswa menutup mata dan tidak peduli, maka sebetulnya “kita sedang membiarkan dan melanggengkan masalah yang menggerogoti dunia pendidikan.”
Marselinus juga menyoroti stigma sosial yang masih begitu kuat yang menilai kepintaran seseorang dilihat dari tinggi atau rendahnya Indeks Prestasi Kumulatif, dan anggapan bahwa “mahasiswa yang berorganisasi pasti tidak serius berkuliah.”
Stigma dan pandangan seperti itu, menegaskan bahwa “feodalisme masih mengakar kuat dalam dunia pendidikan kita.”
“Selama feodalisme masih ada dalam dunia pendidikan kita, jangan harap pendidikan kita akan maju,” katanya.
Ia mengatakan sistem pendidikan di Indonesia masih amburadul dan untuk mengubahnya diperlukan orang-orang yang memiliki idealisme dan mengutamakan kepentingan bangsa masuk dalam sistem kekuasaan.
Ia berharap agar mahasiswa memiliki komitmen dan keberpihakan yang jelas, bahkan berani “melawan arus” untuk melakukan transformasi.
Hal itu, menjadi semakin penting di tengah menguatnya anggapan dalam masyarakat bahwa “semua orang akan melakukan hal yang sama jika sudah masuk ke dalam sistem kekuasaan.”
Sementara itu, Nurul Aliah, mantan Wakil Komisariat Bidang Aksi dan Advokasi DPK GMNI menjelaskan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di negara lain.
Di Finlandia, kata dia, siswa diberi kebebasan untuk menekuni bidang keilmuan yang diminati sehingga “mereka belajar tanpa tekanan.”
Sementara di Indonesia setiap siswa dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran baik umum, peminatan maupun khusus.
“Padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing,” katanya.
Alia juga mengungkapkan bahwa beberapa mahasiswa memilih jurusan bukan karena kehendaknya sendiri melainkan mengikuti kemauan orang tua.
Akibatnya “mereka jarang aktif di kelas dan tidak memiliki gairah belajar.”
Vansianus Masir merupakan Reporter Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa [STPMD] “APMD” Yogyakarta.
Editor: Herry Kabut