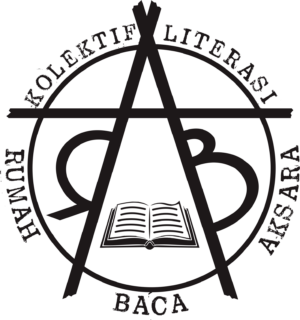Sampah yang berserakan sudah menjadi pemandangan yang biasa kita jumpai saat ini di sudut-sudut kota dan desa. Jalan raya, kali, pantai, pasar dan fasilitas umum lainnya dipenuhi tumpukan sampah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 menunjukkan empat dari sepuluh daerah kabupaten/kota terkotor di Indonesia berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keempatnya adalah Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada.
Penilaian ini berdasarkan beberapa faktor, antara lain kondisi fisik daerah dan Tempat Pemrosesan Akhir. Daerah-daerah terkotor itu mendapat nilai jelek karena melakukan pembuangan terbuka atau open dumping, serta ada yang tidak memiliki kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga.
Faktor lainnya adalah kurangnya komitmen pemerintah daerah, anggaran serta partisipasi publik.
Sayangnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan juga termasuk penyumbang sampah di daerah-daerah itu. Alih-alih berbeda dari lingkungan lainnya, pemandangan sampah yang berserakan juga tampak di sekolah-sekolah, tempat kumpulan insan terdidik. Banyaknya orang atau peserta didik ditambah dengan tidak adanya penanganan sampah yang baik di sebagian besar lembaga pendidikan menjadikan masalah ini sepertinya akan menjadi bom waktu di kemudian hari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Nusa Tenggara Timur berada di angka 96,03, berbeda hanya 1,59 di bawah rata-rata nasional sebesar 97,62.
Data ini menunjukan hampir seluruh masyarakat di NTT yang berada pada usia sekolah sudah mengenyam pendidikan, baik yang sedang berproses maupun yang sudah tamat dari lembaga pendidikan formal, nonformal maupun informal.
Artinya, besarnya angka partisipasi sekolah tidak berbanding lurus dengan kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan teratur, apalagi membayangkan kesadaran itu bertransformasi menjadi budaya pengelolaan sampah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Kondisi ini seharusnya menjadi pukulan yang mencoreng lembaga pendidikan kita karena sistem pendidikan yang belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Alhasil, output pendidikan juga belum mampu menjadi teladan dan rujukan bagi perilaku hidup bersih di tengah masyarakat.
Sekolah: Laboratorium Pengabdian Masyarakat
Salah satu titik lemah sekolah sebagai lembaga pendidikan, hemat saya, adalah kecenderungan menjaga jarak dari kehidupan bermasyarakat.
Saya mengambil contoh sederhana dari apa yang terjadi di lingkungan sekolah selama pandemi Covid-19. Sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dan belajar di rumah, sehingga proses penilaian tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Penilaian yang mengukur ranah kognitif mungkin dilaksanakan, sementara penilaian sikap dan keterampilan sepertinya sulit.
Padahal, justeru sikap dan keterampilan sebagai bagian penting dari karakter peserta didik menjadi hal paling krusial ketika berada di tengah masyarakat. Lengahnya perhatian pada poin-poin ini menciptakan output yang tidak teruji secara karakter. Alhasil, hidup di tengah komunitas masyarakat akan menimbulkan shock atau kaget, terutama karena situasi yang baru itu juga merupakan ‘lumbung masalah’.
Karena itu, lembaga pendidikan hendaknya merumuskan kegiatan yang merangsang dan mendorong para peserta didik untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dengan mengadakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seluruh tingkatan pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu strategi dalam proses penilaian sikap maupun keterampilan.
Saya mengambil contoh penerapan konsep pengabdian kepada masyarakat [PKM] ini dari pengalaman SMP Negeri 1 Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020 hingga sekarang.
Setelah pindah tugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 14 Satar Mese, saya juga menggagas konsep PKM sejak awal 2024. Kegiatan PKM ini telah menyasar dua desa di sekitar sekolah, yaitu Desa Ulu Koak dan Desa Tado, Kecamatan Satar Mese, serta menyebar di beberapa dusun sesuai dengan penyebaran tempat tinggal peserta didik.
Pengabdian yang dimaksud adalah mewajibkan seluruh peserta didik untuk melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, baik secara mandiri maupun secara kelompok terbatas berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Peserta didik juga mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk foto dan video, serta setiap kegiatan ditandatangani oleh pemangku kepentingan mulai dari tingkat RT hingga lurah atau kepala desa.
Jika konsep ini dilaksanakan secara bersama oleh seluruh lembaga pendidikan, tentu ada nilai tersendiri bagi peserta didik, termasuk berdampak pada pola kebiasan masyarakat pada umumnya.
Saatnya lembaga pendidikan harus dijadikan laboratorium mini tempat tumbuh dan berkembangnya nilai moral-spiritual, ilmu pengetahuan, etika serta nilai estetika, agar dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi berbagai persoalan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dengan konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Eks Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, seharusnya lembaga pendidikan dirangsang untuk terus berinovasi menemukan solusi masalah sosial, yang tentu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
Konsep ini sejalan dengan program terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang telah memperkenalkan tujuh kebiasaan baru anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah kebiasaan peserta didik untuk hidup bermasyarakat.
Tanggung Jawab Semua Pihak
Bagi saya, sampah di lingkungan sekolah adalah ironi. Bukannya menjadi laboratorium kehidupan sosial, di mana para peserta didik dibentuk menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran akan persoalan sosial, termasuk sampah.
Berhadapan dengan situasi itu, hemat saya, semua pihak mestinya merasa bertanggung jawab.
Selain lembaga pendidikan, peran masyarakat, terutama lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para aktivis lingkungan selama ini telah terbukti dalam menyebarluaskan pendidikan tentang cara menjaga dan merawat ekologi.
Sementara itu tugas pemerintah yang paling penting sebetulnya adalah menyiapkan regulasi, anggaran dan menggerakan perangkat-perangkat yang dimilikinya untuk terus melakukan sosialisasi terkait kesadaran akan masalah sampah.
Perangkat-perangkat pemerintah di daerah juga harus dapat mencerminkan semangat kerja keras dan tanggap terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.
Secara lebih luas, semua upaya ini terkait dengan paradigma pembangunan yang sudah bergeser dari konsep “dari atas ke bawah” [top down], di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan atau keputusan untuk masyarakat dan tugas masyarakat adalah mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut, menjadi “dari bawah ke atas” [bottom up]. Paradigma baru memungkinkan masyarakat memiliki ruang untuk merumuskan apa yang menjadi permasalahan, keinginan, kebutuhan di lapangan untuk disampaikan kepada pemerintah untuk menghasilkan suatu keputusan bersama sebagai pedoman dalam hidup bersama.
Bukan saatnya lagi berbagai pihak untuk saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saatnya lembaga pendidikan merumuskan program penanganan sampah dan menjadikan peserta didik sebagai agen dan duta sampah bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Pemimpin serta seluruh insan di lembaga pendidikan hendaknya berperan penting menjadi motor penggerak menghidupkan terciptanya ide, gagasan serta visi yang jauh ke depan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk kemaslahatan bersama.
Artikel ini ditulis Maximus Edon, Kepala SMP Negeri 14 Satar Mese, Kabupaten Manggarai
Editor: Anno Susabun