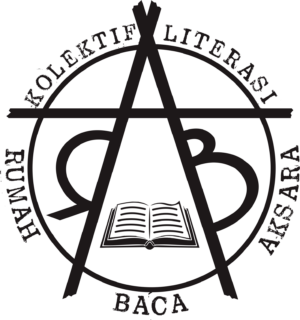Floresa.co – Diskusi yang digelar sejumlah organisasi mahasiswa di Kupang baru-baru ini menyoroti hubungan kuat antara pemerintah dan korporasi yang berdampak pada menyempitnya ruang gerak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam.
Berlangsung di Warung Pojok, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang pada 15 November, diskusi itu bertajuk “Kebijakan Politik dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.”
Inisiatornya adalah Ikatan Mahasiswa Hukum Manggarai [IMHM], Himpunan Pelajar Mahasiswa Manggarai Timur [HIPMATIM] dan Ikatan Mahasiswa Borong Kupang [IMBK].
Dipandu oleh Handrisius Grodus, diskusi itu menghadirkan Yohanes Patrick dan Florianus Dasmadi sebagai pembicara, keduanya merupakan alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
Menurut Handrisius, “kebijakan politik memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat hukum adat, apalagi dalam banyak kesempatan negara absen untuk mengakomodasi kepentingan mereka.”
Keberadaan masyarakat adat, kata dia, seringkali terpinggirkan oleh kebijakan pembangunan nasional yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi makro.”
Kebijakan politik seringkali dilematis “karena di satu sisi bisa mendukung keberlanjutan masyarakat hukum adat, tetapi di sisi lain mengancam eksistensi mereka.”
“Pertentangan antara hukum positif dan hukum adat memperlihatkan sikap pemerintah yang terlalu prosedural dan tidak substansial. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan tanah ulayat,” katanya.
Yohanes Patrick berkata, “diskusi terkait masyarakat adat berkisar antara konsep, hak dan batasan, dan eksistensi, termasuk di dalamnya menyangkut pengakuan, regulasi, political will [kemauan politik] peran serta masa depan mereka.”
Masyarakat adat seringkali mengalami “marginalisasi terstruktur di mana mereka ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, mulai dari prosedur pengakuan sebagai subyek hukum yang berbelit-belit, didiskriminasi oleh regulasi sampai pada perampasan hak atas tanah dan/atau hutan adat.”
Ia berkata, relasi pemerintah dan pengusaha yang sangat kuat juga turut mempersempit ruang gerak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, kata dia, sampai saat ini, pengaturan mengenai masyarakat adat masih bersifat sektoral dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.
Hal ini, jelasnya, diperparah oleh ketentuan mengenai domein verklaring yang diadopsi oleh pemerintah Belanda pada 1970. Domein verklaring merupakan prinsip hukum Belanda di mana setiap tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya [eigendom] akan menjadi milik [domein] negara.
Patrick menjelaskan, domein verklaring sempat dihapus ketika hadir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, namun kemudian diberlakukan kembali oleh Pemerintah Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
Pemerintah Orde Baru, katanya, juga mengunci keberadaan masyarakat adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Keduanya menghilangkan legitimasi otoritas adat, kata Patrick.
Namun, tambahnya, melalui TAP MPR nomor 10 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta amandemen UUD 1945, pemerintah menegaskan “pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B ayat [2] dan Pasal 28I ayat [3].
Pasal 18B ayat [2] menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Sementara itu, Pasal 28I ayat [3] menyatakan “menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Merespons hal itu, kata Patrick, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [AMAN] melakukan judicial review [uji materi] terhadap UU Kehutanan yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi [MK] Nomor 35/PUU/IX/2012.
“Putusan ini menghilangkan kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara,” katanya.
Patrick berkata, putusan itu memiliki dua makna, yakni “negara mengakui masyarakat adat sebagai subyek hukum yang berhak atas wilayah adatnya” dan “negara mengakui kepemilikan hutan adat sebagai hak dari masyarakat adat yang berada di wilayah adatnya.”
Namun, jelasnya, putusan ini seolah ditentang oleh pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 yang menyatakan “Menteri Kehutanan akan menetapkan hutan adat jika masyarakat hukum adat telah ditetapkan dalam peraturan daerah.”
“Banyaknya aturan sektoral yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat dan menyulitkan mereka dalam mengurus legalitasnya,” katanya.
“Sampai saat ini RUU Masyarakat Adat yang sudah masuk dalam prolegnas sejak 2017 belum disahkan menjadi undang-undang. Hal ini jelas menunjukkan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat adat,” tambah Patrick.
Sementara itu, Florianus Dasmadi berkata, “konflik antara masyarakat adat dengan negara sebetulnya lahir dari perampasan dan eksploitasi lahan besar-besaran oleh korporasi.”
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, sejak 2015 hingga 2023 terdapat 2.939 konflik agraria yang mencakup 6,3 juta lahan masyarakat dan 1,759 korban terdampak.
Konflik agraria menyasar semua sektor, termasuk sektor pertanian sehingga banyak petani yang tidak sejahtera dan menjadi buruh harian lepas.
Korporasi, kata Dasmadi, “selalu saja dibentengi dengan perizinan dari pemerintah dengan dalih peningkatan pertumbuhan ekonomi.”
Ia menyoroti produk hukum pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat adat dan memarginalkan hak-hak mereka serta cenderung mempermudah izin usaha korporasi. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ia juga menggarisbawahi minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan politik, di mana pemerintah cenderung memakai pola top down [atas ke bawah], bukan bottom up [bawah ke atas].
Kecenderungan pemerintah menggunakan pola top down mengakibatkan “kebijakan yang dihasilkan mengangkangi kepentingan masyarakat adat.”
“Ruang hidup masyarakat adat dirampas dan berdampak pada hilangnya sumber kehidupan bahkan kerusakan ekologi,” katanya.
Diskusi yang diikuti oleh sekitar 30 mahasiswa itu diakhiri dengan komitmen bersama untuk mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat serta mengawal kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan.
Editor: Herry Kabut