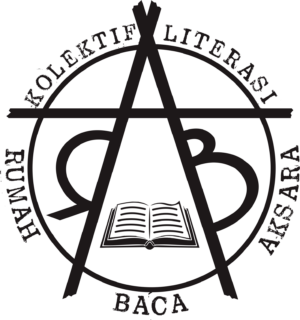Kekuasaan selalu menarik dan menggugah minat untuk meraihnya. Paslah apa yang disampaikan oleh Haboddin [2017], bahwa kekuasaan menggiurkan, menggoda, dan mempesona sehingga siapa saja selalu tertarik untuk mendapatkannya.
Realitas perpolitikan dalam ritual lima tahunan Pemilu mencerminkan secara jelas gairah akan kekuasaan yang begitu kuat.
Sebagaimana kita saksikan, pertarungan merebut kekuasaan dilakukan dengan beragam cara, seolah mengafirmasi apa yang dikatakan salah satu pemikir dalam jagat ilmu politik, Nicollo Machiavelli, bahwa setiap orang dapat menghalalkan segala cara, entah melalui jalan ilegal atau legal, demokratis atau represif untuk merengkuh kekuasaan.
Machiavelli, dalam magnum opus-nya yang tersohor Il Principle [Sang Penguasa], secara radikal membuat dikotomi antara kekuasaan dan moralitas.
Menurutnya, dalam kekuasaan tidak ada ruang bagi moralitas. Ia menyebut nilai-nilai moral merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan kekuasaan adalah suatu realitas yang dihadapi dalam kehidupan setiap hari.
Lebih lanjut, Machiavelli mengafirmasi bahwa penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral.
Dalam urusan politik, yang terpenting adalah bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya.
Tujuan itu dapat ditempuh melalui cara apa pun, baik legal maupun ilegal, demokratis atau represif dan akrobatik irasional.
Misalnya, menyogok penyelenggara Pemilu agar suara bisa digelembungkan, intimidasi, ujaran provokatif dan sarkastis guna mendegradasi rival politik, melakukan kampanye hitam berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan [SARA], tipu muslihat dalam bentuk janji-janji saat berkampanye, dan berselingkuh dengan para oligarki.
Karena tidak ada nilai etis, maka suatu ketika, tatkala kekuasaan telah diraih, seorang pemimpin bisa memperjuangkan kepentingan negara dan kepentingan diri sendiri sekaligus dengan mendobrak konstitusi dan terjebak dalam verbalisme, pragmatisme, dan materialisme.
Ketika kekuasaan telah berada dalam genggaman, berbagai upaya dilakukan agar kekuasaan tetap abadi.
Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Pemilu 2024 baru saja usai. Masyarakat telah mewujudkan hak untuk memilih kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah.
Dengan upaya meraih kekuasaan yang diwarnai dengan beragam upaya yang mengangkangi moralitas, pasca Pemilu, status masyarakat yang beralih dari ‘pemilih’ menjadi ‘penagih janji’ menjadi amat penting.
Sebagai pemilih, masyarakat telah berpartisipasi dalam proses pemungutan suara. Sedangkan sebagai penagih janji, masyarakat mempunyai hak untuk menagih janji politik dan program kerja para kandidat yang sempat mengudara selama kampanye.
Plato, Filsuf Yunani kuno, mengafirmasi bahwa kemajuan dan kemunduran sebuah bangsa ditentukan oleh pemimpin atau para elit politiknya. Mereka memiliki tanggung jawab etis untuk mengarahkan kehidupan bangsanya agar menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.
Namun, tidak sedikit elit politik di negeri ini mengabaikan panggilan mereka sebagai sang pemimpin.
Segenap janji dan program kerja yang telah digaungkan selama kampanye sekadar utopia tatkala kekuasaan sudah berada dalam genggaman.
Mereka mudah terjebak dalam verbalisme, pragmatisme, dan materialisme yang berpotensi mematikan kesadaran akan panggilan sebagai pemimpin.
Verbalisme merujuk pada fakta bahwa seorang pemimpin hanya lihai dalam berkata-kata [Lilijawa, 2010]. Dia bisa menyusun konsep untuk membangun sebuah bangsa, tapi de facto konsep tersebut sebatas utopia.
Dia tak mampu untuk mengubah konsep-konsep tersebut dari probabilitas menjadi realitas. Alhasil, keadaan negara dan masyarakat tidak berubah.
Sementara pragmatisme merujuk pada fakta bahwa seorang pemimpin yang oportunis berpikir tentang untung-rugi dalam menelurkan kebijakan publik.
Dalam hal ini, seorang penguasa mengerahkan koleganya agar menggenggam prinsip ‘kelompok-sentris’, yang memprioritaskan kepentingan mereka dalam mengelola negara dan pada akhirnya terciptanya jurang yang menganga antara kepentingan kelompok dan kepentingan rakyat [Piliang, 2014].
Terjebak dalam materialisme merupakan tingkat kejahatan paling culas, di mana seorang pemimpin lupa pada predikatnya sebagai pelayan publik.
Dia bahkan menempatkan dirinya sebagai kacung keluarga atau pihak tertentu yang dirasa telah berjasa atas kemenangannya, semisal para oligarki.
Di sini, sang pemimpin dan para oligarki akan menjadikan kekuasaan sebagai instrumen demi mendulang profit sebanyak mungkin dan mencaplok apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Wajah sikap para petinggi ini terwujud dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketiga tendensi di atas merupakan referensi teranyar akibat dikotomi moralitas dan kekuasaan dari Machiavelli.
Harapan untuk Para Pemimpin
Berhadapan dengan fakta patologis tersebut, kita mesti mencari model pemecahan agar para pemimpin negeri ini bisa berkiprah di medan kekuasaan dengan mengikuti panduan moral sebagai pemimpin.
Pertama, kesadaran pemimpin akan panggilannya sebagai pelayan publik akan membuatnya bebas dari egoisme dan individualisme, yang memperjuangkan bonum privatio ketimbang bonum communae.
Sebagai pelayan, dia tidak mengejar kekayaan dan mencari hormat.
Kedua, seorang pemimpin mesti independen sehingga dia mampu membebaskan diri dari pengaruh pihak manapun [para oligarki] dalam menelurkan kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat mengartikulasikan kehendak publik, bukan kelompok tertentu.
Seorang pemimpin mesti mendeteksi masalah-masalah mutakhir yang sedang berkecamuk di masyarakat, lalu mencari alternatif solutif untuk mereparasi keadaan yang rusak itu menjadi lebih baik.
Kontrol Lewat Kritik
Untuk memastikan hal di atas terwujud, masyarakat memiliki tanggung jawab etis dalam mengontrol kinerja para pemimpin yang terancam melenceng dari rel yang seharusnya.
Salah satu hak demokratis masyarakat adalah menyampaikan kritik. Kritik-mengkritik di negara demokrasi harus diberi tempat terhormat.
Semua orang bebas menyampaikan kritik secara objektif guna menyadarkan pemerintah agar terhindar dari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika mereka yang berkuasa memakai seperangkat instrumen untuk membungkam kritik, hanya ada satu kata; Lawan!
Wilfridus Fon adalah calon imam Misionaris St. Karolus – Scalabrinian, saat ini sedang kuliah di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere.
Editor: Tini Pasrin