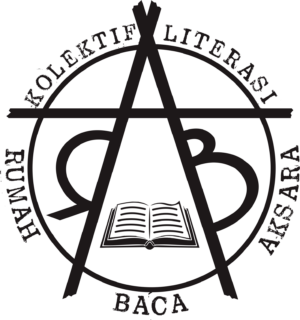Pada 21 Mei, pukul 18.40 Wita, sebuah kabar baik datang dari ujung barat Pulau Flores.
Kabar itu dikirim oleh KoLiterAksi yang merilis pemenang lomba menulis tentang Kurikulum Merdeka kepada khalayak.
Lomba yang mengusung tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka: Sudut Pandang Pendidik dan Peserta Didik di NTT” itu digelar KoLiterAksi- inisiatif kolaborasi Floresa, Sunspirit for Justice and Peace, dan Rumah Baca Aksara – dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Lomba dibagi dalam dua kategori – Artikel Analisis untuk Pendidik SD-SMA/SMK dan Artikel Liputan Mendalam untuk Peserta Didik SMA/SMK. Lomba diikuti oleh 15 kelompok peserta didik SMA/SMK dan 30 pendidik SD-SMA/SMK dari beberapa kabupaten.
Para pemenang, yang diumumkan panitia pada sore itu, tersebar di antara sekolah-sekolah yang berbasis di Pulau Flores dan Pulau Timor.
Di antara puluhan peserta lomba untuk kategori pendidik, saya adalah salah satu yang beruntung. Artikel saya berjudul Harmonisasi Pembelajaran Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Optimalkan Potensi Murid meraih juara I.
Dalam artikel itu, saya bercerita tentang pengalaman pembelajaran di SMA Negeri Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Artikel tersebut menceritakan giat literasi yang kami bangun di sekolah, yang salah satu dampak besarnya adalah pelaksanaan Ujian Sekolah bagi siswa kelas XII berbasis proyek Karya Tulis Ilmiah [KTI].
Proyek itu, yang mulai diterapkan pada bulan lalu, merupakan lompatan besar dalam giat literasi di SMAN Kualin.
Bagi saya, menulis pengalaman sendiri akan melahirkan tulisan yang otentik. Saya mengirimnya ke arena lomba dengan misi berbagi praktik baik terkait pembelajaran, tanpa target apapun.
Omong-omong tentang giat literasi di sekolah, saya teringat pada catatan kritis dewan juri lomba pada kategori pendidik. Beberapa poin penting yang saya rangkum, pertama, apresiasi dewan juri kepada para peserta.
“Peserta merupakan orang-orang yang potensial untuk mengangkat dan membicarakan isu pendidikan di NTT,” kata para juri.
Kedua, terkait konten tulisan, menurut juri, beberapa tulisan disajikan dengan bahasa yang sederhana, inspiratif, mengangkat hal kecil dan sederhana; berusaha menghubungkan fenomena sosial dengan isu pendidikan. Misalnya mengangkat isu pariwisata dan menghubungkannya dengan Kurikulum Merdeka.
Ketiga, masih tentang konten. Para juri menilai ada naskah yang murni opini, hanya berisi klaim dan argumentasi normatif tanpa basis data atau pengalaman. Ada pula naskah yang hanya berisi data dan pengalaman tanpa memberi bobot analisis yang tajam. Ada juga yang berusaha mengkombinasikan opini dan data atau pengalaman, kendati analisisnya tidak cukup mendalam dalam melihat fenomena.
Keempat, dari sisi substansi, dewan juri menyebut sejumlah naskah tidak memiliki pernyataan tesis yang konsisten dalam setiap bagian tulisan dan ada tesis yang kontradiktif pada bagian pendahuluan dan pembahasan maupun kesimpulan.
Kelima, dari aspek tata bahasa, ada naskah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak ada lead atau paragraf awal yang jelas yang dapat memberikan impresi bagi pembaca agar membaca tulisannya sampai akhir. Sebagian besar tulisan juga tidak memiliki kohesi dan koherensi yang kuat antarbagian.
Dari feedback [umpan balik] juri itu, saya menggarisbawahi poin ketiga sampai kelima.
Poin-poin tersebut merupakan feedback berharga dan memantik sebuah pertanyaan, “bagaimana geliat literasi dalam diri para pendidik maupun di ekosistem sekolah?”
Sebagai pendidik, saya lebih suka menjadikan tiga poin itu sebagai sebuah otokritik.
Literasi seharusnya menjadi salah satu standar yang melekat pada diri para pendidik karena profesi ini memerlukan kerja kognisi di level maksimal.
Menjadi pendidik berarti memproduksi ide. Membaca dan menulis adalah cara efektif mengaktivasi otak.
Hal itu terkonfirmasi dari sebuah studi di India yang dilakukan Michael Skeide dan koleganya dari Max Planck Institute for Human Cognitive and Brains Sciences di Leipzig-Jerman.
Studi itu melibatkan 30 orang dewasa, di mana 21 orang diajari membaca dan menulis selama enam bulan, sedangkan sembilan lainnya tidak diajarkan apapun.
Hasilnya, Michael Skeide menemukan bahwa otak para responden menunjukkan perubahan signifikan setelah belajar menulis dan membaca.
Peningkatan ini terjadi pada bagian korteks serebri atau lapisan terluar otak yang terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, peningkatan aktivitas otak juga terjadi di bagian batang dan thalamus.
Bagi saya, membaca dan menulis adalah siklus yang hidup. Tulisan sebetulnya lahir dari proses membaca. Itulah hakikat literasi dasar.
Jika filosofi ini dijalankan dengan baik oleh para pendidik sebagai teladan, maka peluang tumbuhnya kultur literasi di sekolah tentu semakin besar.
Anak-anak memang tidak bagus dalam mendengarkan orang yang lebih tua, namun mereka tidak pernah gagal dalam meniru.
Pemikiran James Baldwin tersebut relevan dengan peran guru sebagai role model bagi murid di bidang literasi.
Muhamad Nasrul Aba Nuen, pendidik di SMAN Kualin, Timor Tengah Selatan; adalah penulis buku “Pendidikan di Mata Guru Pelosok (2020)”
Editor: Herry Kabut