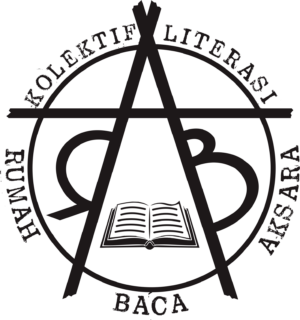Floresa.co – Sabtu pagi, 4 November, GRV pulang sekolah lebih awal dari biasanya. Selama perjalanan ke rumahnya, ia menangis.
TB, salah satu kerabatnya yang kaget melihat GRV lalu bertanya, “Nana (Anak), kau kenapa?” GRV menjawab ia “dipukul oleh kepala sekolah,” sembari menyerahkan sebuah surat.
Isi surat tersebut menjelaskan bahwa GRV, yang sedang duduk di kelas XII SMA Katolik St. Familia Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, tidak lagi bersekolah di sana.
TB lantas bertanya, “Kamu mau pindah sekolah karena kemauan sendiri atau kamu dikeluarkan dari sekolah?” Pertanyaan itu dijawab GRV, “Saya dikeluarkan.”
Awal Mula
Sebagaimana dipaparkan dalam kronologi yang diperoleh Floresa, TB menjelaskan, kasus ini bermula saat Romo Agustinus Hadun, Kepala Sekolah SMA Katolik St. Familia mendapati GRV dan empat orang temannya berkerumun di ruang toilet usai waktu istirahat pertama.
Romo Gusti, panggilan imam itu, kata dia, lalu “mengarahkan empat orang siswa tersebut ke dalam ruang kelas, sementara anak kami, GRV, masih di dalam toilet.” Setibanya di kelas, keempat siswa itu dipukul, demikian pun GRV saat ia kembali dari toilet.
Merespons pemukulan itu, GRV spontan melontarkan kata makian terhadap ayah Romo Gusti, kata TB. Romo Gusti bertambah marah dan bertanya “Kau maki saya”?
TB mengatakan, GRV meminta maaf kepada imam itu, “Maaf Romo, saya salah, saya tidak sadar.” Namun, menurut TB, Romo Gusti menggiring GRV ke toilet, memukul lagi, sambil mengancamnya. “Kau keluar dari sekolah ini,” kata TB, menirukan ucapan Romo Gusti.
Mendengar itu, GRV meminta maaf lagi, tetapi direspons Romo Gusti dengan meninggalkan ruangan toilet, beranjak ke kantor, kata TB. Romo Gusti lalu memberitahukan para guru mengikuti rapat mendadak. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa GRV secara resmi dikeluarkan dari sekolah.
Meminta Maaf Secara Adat
Dengan latar cerita itu, keluarga GRV bersepakat menemui Romo Gusti untuk meminta klarifikasi, sekaligus memohon maaf terkait sikap dan kata-kata GRV. Dengan langkah itu, kata TB, mereka berharap GRV masih bisa bersekolah di sana.
Pada Sabtu sore sekitar pukul 16.00 WIB, mereka tiba di asrama sekolah. Mengenakan pakaian adat Manggarai, mereka membawa satu botol tuak atau arak, simbol permintaan maaf secara adat.
“Saya menaruh satu botol tuak dan satu bungkus rokok di atas meja sebagai tanda penghormatan kepada kepala sekolah atas nama budaya,” kata TB.
Dalam pertemuan itu, kata TB yang menjadi juru bicara keluarga, mereka meminta penjelasan terkait isi surat yang dibawa GRV.
“Setelah kami tanya anak kami GRV tentang alasan pindah, dia bilang bukan kemauan sendiri. Kami heran, itu makanya kami datang bertemu Romo. Karena kalau anak ini punya salah, kenapa tidak panggil kami orang tuanya,” katanya.
Menurut TB, ia menjelaskan kepada imam itu bahwa keluarga menerima jika GRV dihukum karena melanggar aturan sekolah dan menganggap hal itu bagian dari “pembinaan.” Namun, kata dia, keluarga tidak menduga kalau pelanggaran itu mengakibatkan GRV dikeluarkan.
“Apa saja model pembinaan yang diciptakan di sekolah ini untuk anak kami, mungkin itu yang terbaik untuk anak kami. Mungkin itu semua bagian dari bentuk pembinaan. Tapi, kami tercengang setelah baca surat itu,” kata TB.
Mendengar itu, RN, seorang guru yang duduk di samping Romo Gusti merespons. “Sekolah ini ada aturannya. Apa yang dibuat GRV ini bagian dari sikap melanggar aturan, pelanggaran berat, sehingga keputusannya, GRV dikeluarkan dari sekolah,” kata TB menirukan ucapan RN.
Mendengar itu, kata TB, keluarganya bereaksi keras. “Kenapa isi suratnya, seolah-olah anak kami yang mau pindah dari sini. Bahasa di surat ini, bahasa dari anak kami atau dari Bapak,” kata TB. Mendengar itu, RN menjawab “Om, kami yang buat surat ini.”
Setelah mendengar jawaban itu, keluarga GRV meminta RN berhenti berbicara dan memberi kesempatan kepada Romo Gusti untuk memberi penjelasan.
“Dia memaki orang tua saya pada saat saya memberikan sanksi melanggar disiplin,” kata TB menirukan ucapan Romo Gusti.
Mendengar itu, keluarga meminta kebijaksanaan imam itu. “Bagaimana yang bijaknya sekarang? Kami hanya mau minta kebijakan atas kehadiran kami,” kata TB. RN segera merespon dan menegaskan “keputusan sudah final, tidak bisa diganggu gugat.”
Mendengar itu, keluarga GRV memutuskan pamit dan menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. “Baik sudah, kasus ini kami dorong ke proses hukum,” kata TB.
Melakukan Visum dan Melapor ke Polisi
Sepulang dari asrama sekolah, keluarga membawa GRV untuk visum di Puskesmas Wae Nakeng. Setelahnya, mereka memberi keterangan dan pengaduan di Polsek Lembor.
Tidak lama setelah menyampaikan laporan itu, kata TB, anggota Polsek Lembor berkoordinasi dengan Romo Gusti, di mana imam itu akhirnya berinisiatif untuk menempuh jalur damai. Polsek Lembor pun segera menginformasikan kepada keluarga GRV.
TB mengatakan pada Selasa, 7 November, pukul 17.00 Wita, Romo Gusti bersama RN mendatangi keluarga GRV. Mereka membawa satu botol tuak, satu bungkus rokok, dan sebuah amplop berisi uang – sebagai simbol pengakuan salah dan permintaan maaf dalam adat Manggarai.
Berbicara di hadapan keluarga, kata dia, RN mengatakan bahwa mereka bermaksud “meminta maaf dan berharap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan.”
Menurut TB, keluarga merespons permohonan itu dengan menjelaskan bahwa kasus itu telah diproses ke ranah hukum. “Kami kali lalu pergi mencari jalan keluar, ternyata tidak ketemu. Akhirnya, kami bawa masalah ini ke polisi. Kini, Romo datang ke sini,” kata TB.
Romo Gusti merespons dengan berkata, “Bapa, sebenarnya saya datang ke sini dengan berat hati, karena tidak mungkin ada akibat jika tidak ada sebab. Ada api, ada asap.”
Mendengar itu, kata TB, salah satu keluarga GRV geram, sambil berkata, “Kau punya kalimat bikin kami panas saja. Kenapa datang ke sini kalau tidak ikhlas.”
Mendengar itu, TB mengatakan ia berdiri dan meninggalkan tempat mediasi. “Saya terpancing sekali,” kata TB, terutama dengan sikap kepala sekolah yang datang tanpa niat yang tulus.
Yostan Lobang, Kapolsek Lembor yang berbicara kepada Floresa pada Senin, 13 November mengakui bahwa kasus itu telah diselesaikan dengan cara mediasi antara keluarga GRV dan kepala sekolah.
“Sudah ada perdamaian antara pelaku, pihak kepala sekolah dan korban sehingga dari Polsek tempuh jalur restorative justice,” kata Yostan, merujuk pada upaya penyelesaian kasus lewat mediasi.
Yostan mengatakan restorative justice dilakukan atas permintaan kedua belah pihak.
Dengan demikian, jelasnya, “penanganan perkara tindak pidana selesai karena pada intinya kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan dan tidak menuntut untuk diproses hukum.”
Pendisiplinan dengan Kekerasan Sudah Tak Lagi Relevan
Kasus kekerasan seperti ini terjadi di tengah langkah pemerintah mengakhiri praktik kekerasan di sekolah. Pada 8 Agustus, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim bahkan meluncurkan sebuah peraturan khusus terkait upaya melawan praktik kekerasan di sekolah.
Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan itu merupakan bagian dari rangkaian program Merdeka Belajar dan menjadi payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan.
“Peraturan ini lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban,” demikian menurut Kemdikbud.
Berbicara dalam acara bertema ‘‘Negara Hadir Atasi Darurat Kekerasan Anak’ di Jakarta, pada 13 November, Catharina Muliana, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan salah satu tantangan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak ini adalah tidak adanya kesamaan pandangan terkait kekerasan terhadap anak.
Bahkan dalam konteks pendidikan, kata dia masih ada yang menganggap kekerasan “bagian dari pendidikan”
“Guru mendisiplinkan anak dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka, mengakibatkan sakit. Bukan berarti anak tidak boleh mendapatkan sanksi fisik, bisa. Tetapi jangan sampai sanksi fisik itu menyebabkan luka atau menimbulkan sakit pada anak,” ujarnya.
Chatarina mengakui faktor kultur menjadi penyebab langgengnya anggapan kekerasan sebagai bagian dari pendidikan ini. Ia menyebut di kawasan timur Indonesia – wilayah yang juga mencakup NTT – masih ada adagium ‘di ujung rotan ada mutiara’.
“Faktor budaya itu juga menjadi tantangan dalam mengubah mindset guru-guru yang lahir dari produk-produk yang mengandung kekerasan. Kita tidak mudah juga mengubah mindset, seperti membalikan telapak tangan,” ujarnya.
Menurut Chatarina, penting sekali “kita tidak mewariskan pendidikan yang mengandung kekerasan kepada anak pada zaman ini.’
Upaya melawan kekerasan di sekolah ini digalakkan di tengah jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi.
Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan dari hasil survei yang mereka lakukan bersama Badan Pusat Statistik, kendati ada tren penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun, namun secara keseluruhan angkanya masih mencapai puluhan juta.
“Dalam data 2021, masih terdapat fakta bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual,” ujarnya.
Ia juga memberi catatan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap selama ini seperti fenomena puncak gunung es, fakta yang tak terungkap bisa jadi jauh lebih banyak.
Bagaimana Kata Umat?
Dengan gagalnya upaya pendekatan kepada kepala sekolah, GRV telah pindah sekolah. Ia melanjutkan pendidikan SMA-nya yang tinggal beberapa bulan lagi di SMA Negeri 2 Lembor.
VS, seorang alumni SMAK St. Familia Wae Nakeng yang berbicara kepada Floresa pada Senin, 13 November menyayangkan tindakan Romo Gusti, yang ia sebut “terlalu baper menyikapi persoalan yang menurut saya remeh-temeh, hanya karena murid refleks mengeluarkan kata-kata kotor.”
AG, seorang umat Paroki St. Familia Wae Nakeng, juga berkata, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para guru, GRV sebetulnya merupakan siswa yang jarang melakukan pelanggaran di sekolah.
“Di luar makian yang merupakan reaksi spontan, ia bersih dari catatan pelanggaran di sekolah. Dia tidak pernah bolos, tidak aneh-aneh di sekolah,” kata AG, yang mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa guru.
AG mengkritisi sikap kepala sekolah yang mengeluarkan GRV, apalagi dengan merekayasa isi surat sehingga seolah-olah GRV yang mengundurkan diri.
Dengan sudut pandang relasi antara umat dengan Gereja, sebagai pemilik sekolah itu, kata AG, muncul pertanyaan, “apakah Gereja itu anti kekerasan?”
AG mengatakan kasus ini bertentangan dengan klaim Gereja tentang pentingnya menjaga martabat anak. Apalagi, kata AG, Keuskupan Ruteng telah menetapkan 2023 sebagai tahun ramah anak.
Kasus ini, kata dia, juga akan menimbulkan ketidakpercayaan umat terhadap Gereja, khususnya imam, karena apa yang dikatakan dalam khotbah-khotbah “berbanding terbalik dengan yang dilakukan.”
AG memberi catatan bahwa dengan mengkritik Romo Gusti, “bukan berarti kita membenci dan anti Gereja,” tetapi “semata-mata karena kita sayang dengan Gereja.”
Umat, kata dia, mempunyai hak dan otoritas yang sama untuk memperhatikan Gereja, termasuk sikap dan tingkah laku tokoh agama.
Anggapan bahwa “apapun yang dilakukan oleh imam adalah sesuatu yang suci dan bisa dibenarkan,” kata AG, mesti ditanggalkan.
Yayasan Turun Tangan
AG berharap Gereja Katolik, baik Yayasan Persekolahan Umat Katolik Manggarai Barat [Yasukmabar] yang menaungi SMA Katolik St. Familia Wae Nakeng maupun Keuskupan Ruteng mengambil sikap yang tegas terhadap Romo Gusti.
“Misalnya, dia harus pindah dari sekolah itu. Mungkin lebih baik diarahkan ke tempat yang lain dulu supaya dia melakukan refleksi secara pribadi,” katanya.
“Dia harus digantikan kepala sekolah yang lain,” katanya, mengingatkan bahwa karakter tempramental imam itu bisa berbahaya.
Floresa telah menghubungi Romo Gusti berkali-kali lewat WhatsApp-nya untuk mendengar cerita versinya tentang kasus ini.
Namun, hingga pesan terakhir yang dikirimkan pada Rabu, 15 November, ia tidak merespons. Pesan yang terkirim via WhatsApp sudah centang dua.
Sementara itu, Romo Rikardus Mangu, Ketua Yasukmabar mengatakan sedang memberi perhatian pada kasus ini.
“Yayasan dan Paroki Wae Nakeng sedang berproses dalam rangka penyelesaian menyeluruh,” katanya kepada Floresa, Rabu, 15 November.
Imam yang juga Vikaris Episkopal Kevikepan Labuan Bajo itu menjelaskan, “pihak terkait sudah diambil keterangannya.”
“Proses penyelesaian secara adat sudah dilaksanakan dan para pihak sepakat untuk saling memaafkan dan berdamai,” katanya.
Rikardus mengatakan, pihaknya juga “sedang berproses bersama rekan guru dan komite sekolah, lalu hasilnya nanti kita serahkan ke pihak Keuskupan.”
“Yang pasti bahwa Yasukmabar sangat menyesal terjadi kasus seperti ini di tengah gencarnya usaha dan keterlibatan Gereja dalam usaha mendorong gerakan sekolah ramah anak dan paroki ramah anak selama ini,” katanya.
Ia berharap, dengan kasus seperti ini, perlu ada diskusi kritis tentang berbagai kasus kekerasan dalam lembaga pendidikan dan potensi pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh pihak guru maupun kepala sekolah.