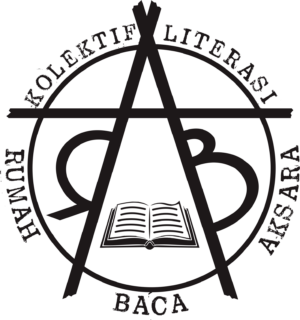Suatu hari, sekolah kami dikagetkan oleh kecelakaan yang menimpa salah satu siswa. Saat itu, seluruh penghuni kelas baru saja menuntaskan proses belajar mengajar pada tiga jam pembelajaran, sebelum istirahat pertama.
Kejadiannya bermula saat siswa itu tengah bermain di dalam ruang kelas. Dari kesaksian teman-temannya, ia melompat dari atas meja. Namun, terjadi pendaratan yang tidak sempurna. Kaki kirinya tergelincir dan patah.
Tentu saja hal semacam ini amat tidak diharapkan terjadi saat anak-anak berada di lingkungan sekolah.
Kejadian ini sontak menggegerkan warga sekolah. Para guru huru-hara. Tanpa membuang-buang waktu, guru piket langsung mengambil sikap. Ditemani oleh tiga orang guru, ia menggendong siswa itu ke pusat pelayanan kesehatan yang terletak tidak jauh dari sekolah.
Tim medis kemudian mengambil tindakan. Tangisan dari bocah laki-laki yang tengah duduk di kelas dua Sekolah Dasar ini memecah kesunyian. Perasaan gelisah menghiasi wajah guru-guru yang turut mengantarnya.
Alhasil tim medis berhasil memberi perawatan, sesuai sumber daya yang ada.
Selanjutnya anak ini diantar menuju rumah dari kerabat dekatnya untuk dirawat. Proses perawatan kemudian dilakukan secara tradisional. Selama di rumah kerabat ini, kaki siswa ini dikompres dengan kunyit yang telah diparut. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan saat pagi dan sore hari, sembari tetap meminum obat yang diberikan tim medis.
Setelah tiga hari dirawat di rumah kerabatnya, anak ini kemudian diantar ke rumah warisan orangtuanya. Saya dan guru wali kelasnya ikut mengantarnya.
Sebelum berangkat, kami berkoordinasi dengan pihak medis untuk memberikan perawatan lanjutan. Saat memohon agar anaknya disuntik, pihak medis menyarankan untuk rutin minum obat saja. Kami ikut saran itu.
Satu-satunya alat transportasi yang tersedia saat mengantarnya adalah sepeda motor. Anak ini dibonceng oleh kerabatnya.
Sepanjang perjalanan ada kalanya ia teriak kesakitan saat guncangan di atas motor begitu kuat, buntut dari jalanan yang amat buruk.
Pada saat tertentu kami membetulkan kakinya agar kembali ke posisi semula, sekaligus membantunya untuk menghindari guncangan.
Kami tiba di tempat tinggalnya setelah melalui drama yang melelahkan, melewati jalanan buruk dengan batu-batu yang berserakan di badan jalan.
Yang membuat ceritanya semakin dramatis, anak ini ternyata dari keluarga yatim. Ayahnya telah meninggal. Ibunya merantau ke Malaysia.
Kabar yang terdengar dari mulut ke mulut, di Negeri Jiran itu ibunya telah memiliki pasangan. Ibunya kadang mengirim uang. Perhatiannya, dalam pikiran saya, tentu terbagi, antara mengurus keluarganya di sana dan memerhatikan anak-anaknya di sini.
Anak ini tinggal dengan dua kakak perempuannya. Satunya duduk di kelas lima, satunya lagi telah berkeluarga.
Di rumah itu, kami dilayani oleh kakaknya yang kelas lima itu. Kebetulan ia pulang bersama kami dari sekolah.
Kakaknya yang sudah bersuami tengah bekerja di kebun milik orang sebagai buruh harian. Sementara suaminya turut menjemput adik iparnya itu.
Pasangan suami isteri ini masih muda. Mereka baru mulai menata rumah tangga.
Pada perjalanan pulang, saya merenung.Jiwa aktivis saya meronta-ronta,menangis melihat situasi yang dialami oleh keluarga kecil yang saya kira belum sanggup memikul beban begitu besar.
Saya kemudian berbagi cerita dengan teman guru yang turut mengantar anak tersebut.
“Kadang Tuhan tidak adil, keluarga sederhana itu diberi tantangan yang mungkin berat untuk mereka pikul.” Saya pikir saat itu, Tuhan benar-benar berlaku tidak adil.
Salah satunya dalam kasus siswa ini, maupun di dalam cerita-cerita lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beban bertubi-tubi yang justeru diletakkan di pundak mereka yang sudah kesusahan.
Namun, segera saya sadari bahwa tugas kita kadang mungkin cukup kuatkan ayunan langkah untuk terus melaju. Dan, saat menyadari ada yang mengalami situasi seperti itu di sekeliling kita, yang dibutuhkan adalah, jika memungkinkan, membangun solidaritas dan mencari cara, apapun bentuknya, untuk membantu. Jadi, tidak hanya berhenti pada kecewa, rasa putus asa.
Hal itu yang kemudian coba saya lakukan berhadapan dengan situasi anak itu.
Dua hari kemudian setelah mengantarnya, saya berbagi cerita tentang kondisinya di media sosial. Dua orang baik mengajukan tanya di kotak pesan. Mereka menanyakan dengan rinci kondisi anak itu. Kemudian mereka mengantar bingkisan dan sedikit rupiah untuk disumbangkan pada anak tersebut.
Keesokan hari setelah menerima bingkisannya, kami menyerahkan titipan orang baik tersebut lewat kakaknya yang masuk sekolah.
Sesuai pesan dari salah satu orang baik tersebut, saya turut mengecek uang komite dari anak tersebut di bendahara komite sekolah. Setahun ke depan, dia yang membayar uang komite nya.
Saat saya menulis ini, anaknya sudah kembali bersekolah dengan normal setelah menjalankan cuti selama dua bulan. Ia kini dapat berjalan dengan normal, tanpa ada hambatan dalam proses perawatannya.
Tuhan berlaku adil pada akhirnya untuk anak ini.